Saat tinggal di suatu pedesaan antara Gunung Gede dan Gunung Salak yang masih asri. Menikmati dinginnya udara khas pegunungan yang semilir menerpa wajah, kami berkumpul di saung setelah lelah berlatih salah satu silat tradisional. Nikmatnya singkong goreng yang masih basah oleh minyak panas, ditaburi penyedap rasa untuk menambah kelezatannya dan teh panas untuk mengalahkan hawa pegunungan yang menusuk. Perlahan-lahan kuhirup teh yang masih berasap, rasanya seperti ada bara api di lidah, menggoyahkan kerongkongan yang sedari tadi menunggu air mengalir.
Sembari asyik menikmati cemilan, Uwak Buyut yang sedari tadi asyik berbicara, mulai bercerita mengenai batu-batu yang berada di kaki Gunung Salak yang dia kunjungi beberapa waktu silam. Batu-batu tersebut konon merupakan peninggalan Kerajaan Salakanagara. Mendengar hal tersebut, saya tertarik mendengar penuturan Uwak mengenai kerajaan Salakanagara lebih lanjut. Teman-teman disekitar juga ikut merapat mendengarkan. Kisahnya terus berlanjut sampai Uwak mengisahkan Salakanagara adalah kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Konon, Kerajaan Salakanagara sudah berdiri sejak abad ke-2 Masehi, jauh lebih dahulu ketimbang Kerajaan Kutai Martadipura yang baru berdiri sejak abad ke-4. Meskipun diklaim lebih dahulu berdiri, sampai sekarang belum ada temuan lebih lanjut yang bisa melegitimasi pernyataan tersebut.
Mendengarkan cerita, mitos, atau legenda memang lebih seru ketimbang mendengar penjelasan ilmiah yang kadang justru membosankan dan membingungkan. Terlebih legenda dapat membangkitkan imajinasi menjadi lebih aktif dan liar daripada pemaparan ilmiah. Mungkinkah ini sebabnya penjelasan non ilmiah lebih digandrungi oleh masyarakat?
Pertanyaan ini berlanjut ke meja kuliah yang mana waktu itu diisi oleh Irmawati Marwoto-Johan, salah satu dosen arkeologi Universitas Indonesia yang menjelaskan tentang arkeologi alternatif.
"Masyarakat punya interpretasi sendiri dalam memaknai tinggalan arkeologi, jadi meskipun tidak berlandaskan ilmiah, interpretasi itu tetap harus diberi ruang sendiri" jelasnya. Hal inilah yang mendasari para ahli mengamini arkeologi alternatif sebagai bagian pseudo scientific archaeology.Dalam jurnalnya, Irmawati Marwoto-Johan menjelaskan penggunaan kata arkeologi alternatif dicetuskan oleh Tim Schadla-Hall (2004) sebagai padanan pseudo scientific archaeology ataupun fantasy archaeology yang mana hal ini lekat dengan penafsiran masyarakat awam atas benda cagar budaya yang ada di sekitar mereka.
Lantas dimanakah posisi arkeologi alternatif dalam ilmu arkeologi dan masyarakat indonesia?
Kebanyakan arkeolog menolak interpretasi yang di berikan oleh non-arkeolog. Mengapa begitu? Sebab pada dasarnya pengetahuan yang diberikan oleh para arkeolog sudah melewati tahapan ilmiah yang panjang sebelum menjadi suatu kesimpulan. Layaknya ilmu yang berkembang, kesimpulan ini boleh dibantah dengan penelitian selanjutnya yang juga berlandaskan ilmiah. Maka langkah arkeologi alternatif dinilai sebuah penyimpangan yang jauh mendekati kata "benar" karena hanya berlandaskan mitos atau legenda yang keabsahannya tentu diragukan.
Keberadaan mitos-mitos di suatu benda atau bangunan termasuk kepercayaan lama yang ada di Indonesia, jauh sebelum ilmu arkeologi berkembang. Hal ini akhirnya menjadi legenda di suatu benda/tempat yang berakhir dengan pengeramatan. Bahkan tak jarang saking angkernya suatu tempat, penelitian ilmiah sering dihalang-halangi agar penduduk sekitar tidak mendapatkan bencana apabila mengganggu tempat tersebut. Tentunya interpretasi masyarakat tersebut tidaklah bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat mereka hidup berdampigan dengan cagar budaya tersebut.
Arkeolog rupanya sudah memperhatikan aspek kedekatan masyarakat dengan benda cagar budaya; meletakkan hubungan mereka dalam harmoni saat pendataan namun juga berupaya untuk mengesampingkan fakta serta mitos dari masyarakat setempat. Hal inilah yang mengukuhkan status arkeolog sebagai interpreter utama. Malangnya, informasi penelitian yang harusnya menjadi konsumsi masyarakat hanya berakhir ditumpukan jurnal dan berakhir sesak di perpustakaan. Tak jarang ilmu-ilmu yang terangkup dari kertas berakhir di tangan pengepul ataupun penjual gorengan.
Alhasil untuk memuaskan dahaga ketidaktahuan, maka masyarakat mulai berpaling kepada interpreter-interpreter yang lebih membumi. Paranormal, dukun atau sekarang populer juga dengan sebutan indigo. Masyarakat akhirnya mengesampingkan produk ilmiah dengan bahasa yang rumit dan mulai melihat penjelasan supranatural sebagai penjelasan utama. Perspektif masyarakat dalam menilai cagar budaya sangat dipengaruhi lingkup tempat tinggal serta pengalaman dalam berinteraksi dengan cagar budaya.
Sebagai contoh kasus arkeologi alternatif adalah situs Trowulan yang penelitiannya terus dilakukan dari tahun 70 sampai sekarang, kurang mendapat antusias masyarakat dalam ulasan arkeologi. Situs Pendopo Agung misalnya yang dibangun oleh Kolonel Sampurna dianggap masyarakat sebagai pendopo keraton tempat Raden Wijaya dan juga pertapaannya. Banyak masyarakat yang berziarah dan bersemedi sembari memohon tuah dari tempat tersebut. Lain halnya dengan situs Siti Inggil yang dianggap sebagai makam Raden Wijaya dan istrinya, meskipun tidak ada bukti ilmiah, namun kepercayaan masyarakat akan makam tersebut sangat kuat. Sama halnya dengan Gunung Padang yang dianggap masyarakat sebagai piramida dan dikeramatkan.
Gambar 1. Pendopo Agung ( Sumber: Welly
Handoko/travellingyuk.com)
Gambar 2. Siti Inggil yang diyakini masyarakat sebagai
makam Raden Wijaya (Sumber: Dinas Pariwisata Mojokerto/disparpora.mojokertokab.go.id
Selain masyarakat umum, ada beberapa kelompok yang menunjukkan eksistensinya dalam menilai benda cagar budaya dengan kacamata pseudo science, yang paling terkenal adalah Turangga Seta, komunitas pencinta sejarah dan budaya. Mereka banyak menafsirkan cagar budaya tanpa didasari narasi ilmiah atas ketidakpuasan terhadap tafsir sejarawan maupun arkeolog. Mereka memilih dupa dan roh leluhur sebagai medianya. Selain itu, terdapat pula interpretasi arkeologi alternatif yang sudah dibukukan semisal buku tentang Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman.
Dengan mudahnya masyarakat melakukan penafsiran, benda cagar budaya menjadi lebih rawan rusak atau penyimpangan sejarah demi pemantapan tafsir seperti kasus prasasti palsu Sungai Ci Mandiri Sukabumi, penggalian Gunung Padang, ataupun kasus lainnya.
Gambar 3. Prasasti palsu yang diklaim ditemukan di
Sungai Ci Mandiri Sukabumi (Sumber: Lutfi Yondri/tirto.id)
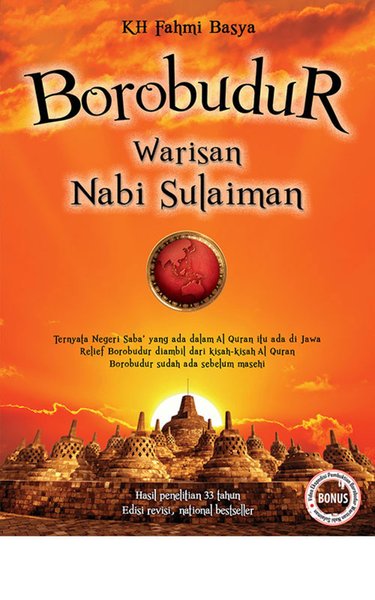
Pada akhirnya, peran arkeolog dalam dekade ini tidak hanya menggali lalu mengolah temuan arkeologi, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam melakukan penafsiran, serta mengedukasi apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap cagar budaya. Sah-sah saja masyarakat ikut andil dalam penafsiran, entah itu penafsiran tunggal maupun kelompok. Interpretasi- interpretasi non arkeolog dimaksudkan untuk memberikan ruang dan melabelkan istilah "alternatif" daripada mengintimidasi mereka dengan mengatakan "palsu".
Jelasnya, apapun penafsiran yang dilakukan, jangan sampai hal tersebut merusak cagar budaya ataupun memalsukan temuan. Barangkali kalau para arkeolog masih merasa kesusahan dalam menjangkau publik, boleh saja menilik arkeologi alternatif sebagai penyampaian informasi sekunder yang diselingi narasi ilmiah yang ringan, dan tentunya tidak keberatan jika dikisahkan layaknya novel.











